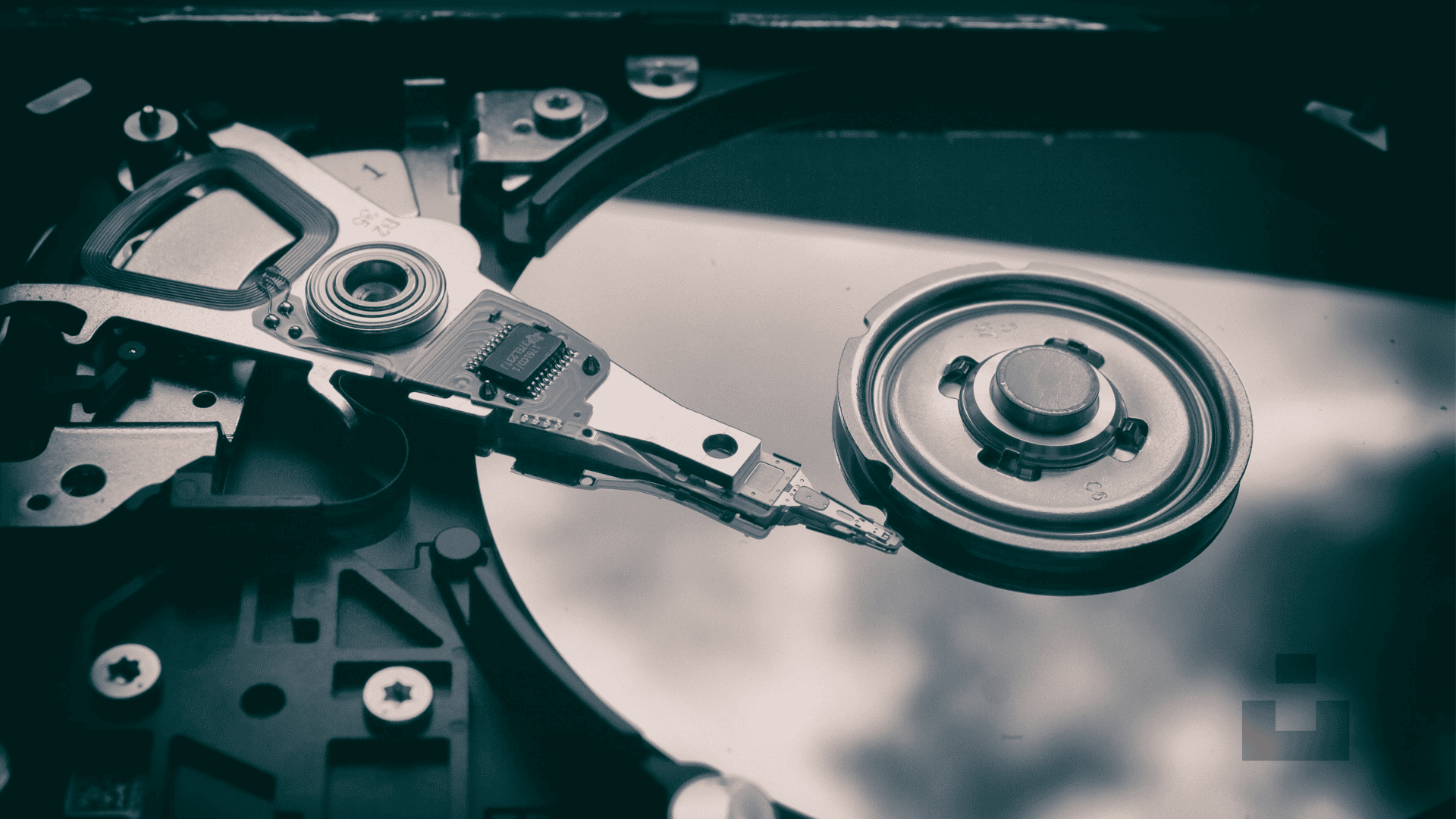Hujan lebat, sapuan angin, genangan air, dan lumpur tak menyurutkan semangat dan niat tulus Sinau Bareng Caknun di Jombang malam itu. Hati para jamaah maiyah tergerak, Allah menggerakkan hati mereka, melangkahkan kaki mendekati cahaya ilahi melalui jamaah, sinau bareng.
Para sedulur-sedulur Maiyah tentu punya pengalaman yang menakjubkan. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Pengalaman dalam perjalan menuju lokasi maiyahan, saat pelaksanaan maiyahan, atau mungkin setelah acara usai.
Seperti malam yang lalu, ketika saya menghadiri Sinau Bareng Caknun dan Kiai Kanjeng di Perak, Jombang. Hujan lebat disertai angin memporakporandakan tenda, air menggenang mengubah tanah jadi berlumpur, dan beberapa sound system macet. Tapi semua itu tidak menyurutkan jamaah maiyah untuk sinau. Sampai acara tersebut selesai mereka tetap duduk—bahkan ada yang tetap tegak berdiri—mengikuti sinau tersebut.
Saya takjub, pertanyaan kecil muncul dari dalam hati, mengapa dan bagaimana hati mereka begitu tergerak untuk tetap jejeg mengikuti Sinau Bareng ini?
Padahal kalau dipikir-pikir, Mbah Nun rutin mengadakan Maiyah di Jombang. Padhangmbulan. Hujan lebat itu seharusnya cukup menjadi alasan untuk tidak hadir di acara malam itu. Toh, Maiyah Padhangmbulan akan diadakandi tanggal 23 Desember mendatang.
Seorang teman, ketika saya ceritakan nuansa maiyah malam itu, memberi komentas seperti: “Inilah yang namanya cinta”.

Kejadian serupa tidak hanya sekali. Barangkali tak terhitung jari lagi betapa hujan dan angin sering datang menghampiri kegiatan maiyah seperti ini. Dan, kecintaan Mbah Nun pada jamaah maiyah selalu menghangatkannya. Yang saya ingat ketika mengalami kejadian seperti ini beliau selalu bilang begini “Hujan ini adalah penyaring ketulusan hati kalian untuk sinau.” Dan lantunan doa-doa dipanjatkan untuk mereka yang gigih itu. Hujan dan angin pun turut khusyuk mengikuti sinau bareng.
Basah dan lumpur terlupakan. Kami khidmat menyimak sinau malam itu. Sesekali dengan canda tawa. Sesekali dengan bernyanyi bersama. Satu dua tembang dari Kiai Kanjeng. Sampai kemudian empat jamaah diajak naik panggung untuk bermain kupatan. Permainan kuna yang tak lagi masyhur untuk dimainkan. Tapi kemudian dari permainan kecil di atas panggung itu kami belajar tentang ketulusan, keselarasan, dan kejujuran.
Kita dipertontonkan betapa gengsi/jaim telah menjadi pakaian para intelektual. Semakin tinggi pendidikan semakin melekat jaimnya. Bahkan untuk sekedar menolong seorang pengendara yang jatuh ke selokan. Hal ini terjadi bersamaan dengan merosotnya nilai ing ngarso suntulodho, ing madyo mangunkarso, tut wuri handayani. Seharusnya, kepemimpinan (menjadi pemimpin karena keilmuannya atau karena dipilih untuk memimpin) dibarengi dengan ing ngarsosuntulodho. Tidak berhenti pada instruksi untuk melakukan sesuatu tapi mengawalinya supaya dipanuti oleh yang dipimpin.
Setelah yang dipimpin menguasai, maka naik ke fase berikutnya: tandang gawe bareng. Bersama-sama menyelenggarakansupaya keselaranan senantiasa terjaga. Hingga pada akhir sampai pada fase tut wuri handayani, menjadi pendukung dan penopang kreatifitas masyarakat yang dipimpinnya.
Menemukan pemimpin yang seperti ini tidak mudah. Ada. Tapi sulit. Apalagi saat ini kewarasan kita diobrak-abrik oleh Jakarta. Apa istimewanya Jakarta hingga akal sehat dan nurani kita terpenjara olehnya? Para elit di sana tidak lagi berpandangan keindonesiaan. Bolehlah kita menjadi simpatisan partai politik tapi jangan terikat pada kepartaian hingga lupa dengan keindonesiaan. Ibarat fans club sepak bola dalam Liga Indonesia mereka boleh fanatik terhadap club kesayangannya. Tapi dalam pertandingan internasional, club tidak ada lagi. Yang ada adalah Indonesia.
Namun, Mbah Nun selalu membangun optimisme di tengah-tengah hingar bingar ini. Begitulah ia. Optimisme itu dibangun karena malam itu, semua yang hadir menanam benih yang oleh sebagian akan dipanen esok hari, sebagianyang lain pekan depan, bahkan mungkin akan ada yang memanen puluhan tahun yang akan datang.
Malam itu kami belajar tentang objektifitas. Tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Tapi di tengah. Mendengar dan melihat yang sebelah kanan dan juga yang sebelah kiri. Jangan nggumunan dan gupek. Santai. Melihat permasalahan di sebelah kanan dan sebelah kiri sebagai permasalahan yang biasa tapi serius untuk ditangani. Dengan objektifitas itu setiap orang bisa dirangkul lalu berjalan dan bekerja bareng-bareng.
Lalu kami disimulasikan. Jamaah dibagi bagi ke dalam dua kelompok. Sebelah kanan menyanyikan lagu Topi Saya Bundar dan sebelah kiri menyanyikan Burung Kakak Tua. Yang berdiri di sebelah kanan akan lebih dominan mendengar lagu Topi Saya Bundar. Begitu sebaliknya di sebelah kanan. Tetapi yang berdiri di tengah? Ia harus mendengar kedua lagu itu bersama-sama. Maka wajar kalau kemudian terdengar lirik lagunya menjadi “burung kakak bundar … …giginya topi saya”
Lalu kami mentadabburi peristiwa kecil itu. Betapa sulit untuk berdiri di tengah. Objektif. Secara adil dan jujur mengatakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Kedua lagu itu sama-sama baik. Tidak perlu dipertentangkan. Tapi ketika komposisinya salah, dicampuradukkan, maka nilai kebaikannya hilang.
Seperti kopi dan garam. Kopi baik, begitu juga dengan garam. Tetapi keduanya tidak bisa dimasukkan dalam satu komposisi karena keduanya nggak gathuk. Sebab, pasangan kopi adalah gula dan pasangan garam adalah sayur.
Menjelang akhir Sinau, Kiai Muzammil mengingatkan kita tentang bangunan keluarga yang sakinah. Di antaranya dimulai dari bangunan rumah yang menaunginya.
Dalam bahasa Arab terdapat beberapa istilah untuk kata “rumah”. Masing-masing kata memiliki arti dan nilainya sendiri. Pertama adalah bait. Secara harfiah berarti tempat bermalam. Seperti kata dalam kata mabit di Muzdalifah. Ada sebagian orang yang menjadi rumahnya sebagai tempat bermalam dan makan. Pagi ia berangkat kerja. Sore kembali ke rumah. Makan lalu tidur.
Kedua adalah maskan. Tempat tinggal dan tempat kita mencari ketenangan. Seperti dalam doa kita kepada orang yang menikah. Rumah tangganya adalah tempat ketenangan. Ia menikah, menempati tempat tinggal, memiliki anak, membina keluarga, dan segala aktifitasnya adalah dalam rangka mencari ketenangan.
Selain bait dan maskan, ada istilah lain untuk menyebutkan rumah. Yaitu dar. Konsep dar lebih besar dari maskan. Ia tidak lagi berbicara pada satu rumah tetapi banyak rumah. Populasi maskan membentuk sebuah lingkungan. Kalau maskan-maskan itu membangun dan membentuk nilai-nilai yang luhur maka dar–perhubungan satu maskan dengan maskan lainnya–akan terbentuk dengan baik pula. Oleh karena itu, untuk menciptakan lingkungan yang baik, tidak lain adalah dengan cara membentuk dar yang baik. Dan pondasi dar yang baik adalah maskan-maskan yang sakinah.
Sinau Bareng ini merupakan media untuk menanam benih-benih kemandirian dan kedaulatan sebagai manusia Nusantara. Kita. Yang saat ini menciptakan optimisme sendiri dari lingkungan yang paling dekat den lekat: keluarga. Benih itu akan bertunas, berakar dalam sanubari, dan bersiaplah memanennya.